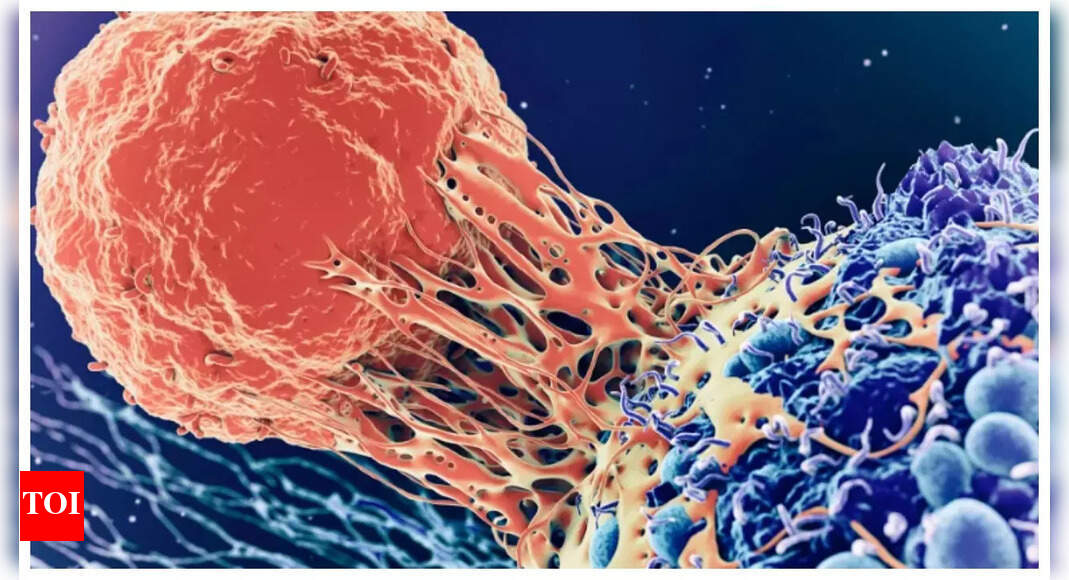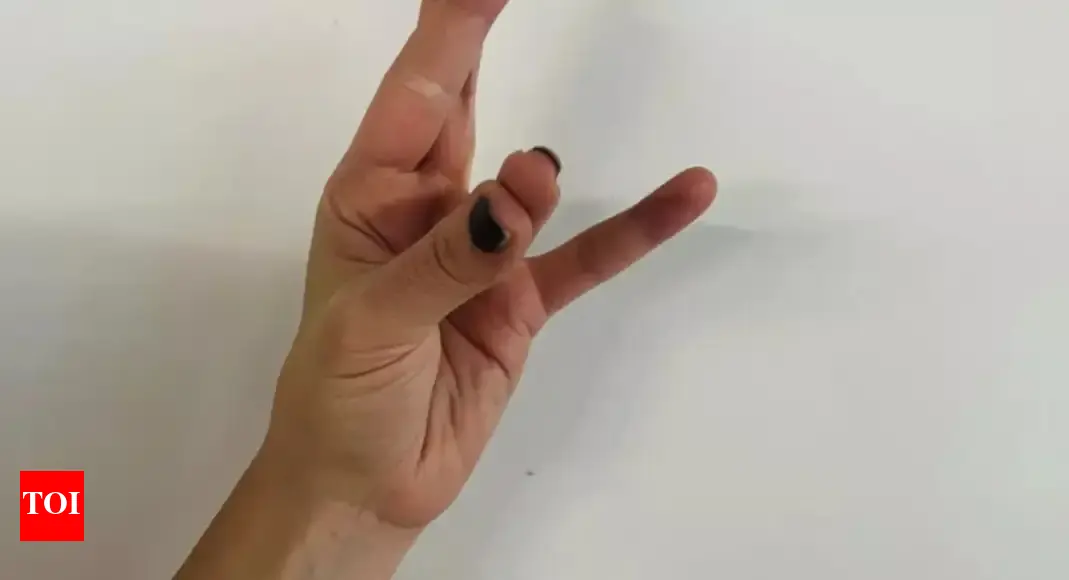Zainab dan Fenomena Penyakit Blackwater Fever di Uganda

Pada usia enam tahun, Babirye Zainab telah mengalami malaria beberapa kali. Namun, neneknya tidak menganggapnya sebagai masalah besar. “Saya biasanya merawatnya dengan obat antimalaria dan dia akan baik-baik saja,” ujarnya.
Suatu ketika, dia mengalami demam tinggi dan mulai mengalami kejang. Urin Zainab berwarna seperti teh, dan neneknya, yang juga bernama Babirye, cukup khawatir untuk membawanya dengan sepeda motor ke pusat kesehatan setempat.
“Kami diizinkan pulang. Sebulan kemudian, dia mengalami episode lain. Sejak saat itu, dia telah mengalami beberapa episode dengan urin berwarna teh,” lanjutnya.
Zainab merupakan bagian dari teka-teki medis yang memengaruhi daerah pedesaan Uganda.
Dia menderita penyakit blackwater fever, yang merupakan komplikasi malaria yang jarang tetapi semakin meningkat, dan sedang dicari penjelasannya oleh para peneliti. Penyakit ini dinamakan demikian karena urin pasien berubah menjadi gelap akibat darah, dan dapat berakibat fatal.
Blackwater fever terjadi ketika sel darah merah pecah secara cepat dalam aliran darah, melepaskan hemoglobin yang kemudian diekskresikan melalui urin. Hal ini dapat mengakibatkan anemia dan jaundice, serta memerlukan transfusi darah.
Profesor Kathryn Maitland dari Imperial College London, yang berbasis di Kenya, merupakan bagian dari tim yang memperhatikan tingginya angka anak-anak di Uganda timur yang mengalami blackwater fever hampir satu dekade lalu. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di jurnal Clinical Infectious Diseases, mereka melaporkan bahwa kondisi ini “menurut penyelidik lokal, jarang terjadi hingga tujuh tahun terakhir” dan berspekulasi “bahwa ini mungkin terkait dengan pengenalan terapi kombinasi berbasis artemisinin”, jenis obat antimalaria paling modern saat ini.
Sejak itu, Maitland mengungkapkan, “kami telah menggali, menggali, dan menggali”, mencari penjelasan lebih lanjut.
Secara historis, blackwater fever terlihat pada ekspatriat Eropa yang mengonsumsi dosis kecil kina sebagai antimalaria, dan menjadi semakin jarang ketika obat lain menggantikan perannya.
Ada satu hal yang sangat menarik dalam kasus anak-anak Afrika: setelah satu kali mengalami episode, mereka cenderung mengalaminya kembali, ungkap Prof. Kathryn Maitland.
“Ini tentu saja tidak disebutkan dalam pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk malaria berat – itu tercatat sebagai kejadian yang sangat jarang. Namun, kejadian tersebut semakin meningkat,” kata Maitland.
Tim risetnya telah menyelidiki kemungkinan penyebab genetik, termasuk apakah gen yang terkait dengan anemia sel sabit atau defisiensi enzim G6PD, yang meningkatkan risiko pecahnya sel darah merah, mungkin terlibat. Namun, keduanya tidak tampak memberikan jawaban yang memadai.
Sebuah teori yang menyebutkan bahwa obat-obatan antimalaria yang digunakan di bagian Uganda yang terdampak mungkin substandar atau palsu telah dibantah melalui pengujian menyeluruh. “Obat-obat tersebut berkualitas baik – jadi kami kembali ke papan gambar,” tuturnya.
Hipotesis terbaik, menurutnya, berdasarkan pengalaman dokter di daerah terdampak, tetap terkait dengan pengobatan malaria berbasis artemisinin.
Presentasi kondisi ini bisa sangat mengkhawatirkan, kata Maitland. Seorang anak dengan blackwater fever yang dirawat di rumah sakit di ibu kota, Kampala, mengalami gejala “mengeluarkan urin merah dan hitam. Ini terjadi pada saat-saat ketika ada Ebola, dan memicu evakuasi – semua ibu melihat ini, mengangkat anak-anak mereka dan berlari keluar.”
Anak-anak yang terdampak “memiliki risiko tinggi untuk meninggal,” jelasnya. Mereka mungkin memerlukan transfusi darah beberapa kali, yang meningkatkan risiko reaksi buruk, dan memerlukan perawatan di rumah sakit.
“Apa yang sangat menarik di kalangan anak-anak Afrika adalah bahwa setelah mereka mengalami satu episode, mereka cenderung mengalaminya berulang kali,” ungkapnya. “Diduga setiap kali mereka terinfeksi ulang dengan parasit malaria, mereka mengalami blackwater fever.”
Zainab mengalami blackwater fever setiap beberapa bulan, menurut neneknya. Sejak berusia delapan tahun, dia tidak dapat bersekolah karena anemia yang dideritanya.
“Saya sering harus membawanya ke fasilitas kesehatan karena kondisi tubuhnya yang lemah. Dia tidak bisa sekolah karena ini,” kata neneknya, yang telah merawat Zainab sejak dia berusia enam bulan. “Ketika dia jatuh sakit, saya bahkan bisa menghabiskan waktu seminggu di rumah sakit.”
Terkadang tidak ada obat yang tersedia, dan keluarganya harus mencari suplai dari sumber swasta. Jika Zainab membutuhkan transfusi dan tidak ada darah yang tersedia secara lokal, mereka harus pergi ke rumah sakit regional “yang sangat mahal”.
Zainab dan neneknya kini menjadi bagian dari program penelitian yang dipimpin oleh Jane Frances Zalwango dari Uganda National Institute of Public Health. Dia memiliki beasiswa dari sebuah perusahaan kesehatan global untuk melacak kasus blackwater fever di Uganda, serta memahami mengapa beberapa anak mengembangkan kondisi ini dan yang lainnya tidak.
Uganda masih membangun sistem surveilansnya, menurut Zalwango, yang berarti angka yang ada tidak komprehensif, tetapi data yang dimiliki menunjukkan adanya peningkatan kasus.
Studi ini telah mendaftarkan 400 anak dari distrik Budaka di Uganda timur, di mana upaya surveilans awal mencatatkan angka tertinggi. Separuh dari mereka mengalami blackwater fever, sementara separuh lainnya pernah menderita malaria tanpa mengembangkan komplikasi. Mereka akan diikuti selama beberapa bulan, dengan pengambilan sampel darah untuk menganalisis penanda imunologis.
Dr. Mary Rodgers, seorang peneliti asosiasi di Abbott, yang programnya merupakan bagian dari Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (Tephinet), mengatakan teori lain yang sedang dipertimbangkan termasuk apakah malaria dalam kombinasi dengan faktor genetik, atau “patogen yang menginfeksi bersamaan yang mungkin tidak membuat orang sakit” terlibat.
Berbicara kepada keluarga selama pendaftaran trial sangat menghancurkan, jelas Zalwango. “Mereka selalu khawatir tentang episode berikutnya.”
Hal ini juga mengungkapkan kepercayaan superstisi yang mengelilingi blackwater fever. “Beberapa tidak mencari bantuan tepat waktu karena kepercayaan tradisional mereka: berpikir mungkin ini adalah sihir atau sesuatu yang lain.”
“Namun, mereka mulai memahami hal ini berkat interaksi mereka dengan tenaga kesehatan, yang mendidik mereka tentang pentingnya mencari perawatan kesehatan lebih awal untuk mencegah kematian akibat episode ini, jadi kami semakin membaik.”
Nenek Zainab berharap penelitian ini akan menghasilkan perawatan yang dapat membantunya: “Para petugas kesehatan memberi tahu saya bahwa ini adalah malaria yang menyebabkan kondisi ini. Namun, Zainab sudah terkena malaria sebelumnya dan tidak mengalami pendarahan dalam urin.”
“Mungkin mereka akan menemukan cara untuk mencegah anak-anak lain mengembangkan kondisi ini,” ujarnya.